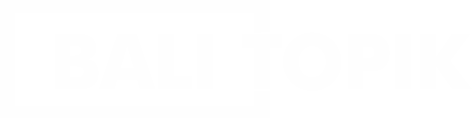Oleh: Pengamat politik, Dosen Fisip UNUD, Efatha Filomeno Borromeu Duarte
Balitopik.com – Di negeri ini, politik bukan lagi urusan rakyat, melainkan urusan para elite yang lihai bermain sandiwara. “Cawe-cawe,” katanya. Sebuah istilah yang terdengar sederhana, seperti tetangga ikut mengatur, mengurusi dan menentukan seluruh resepsi pernikahan. Tapi jangan terkecoh, “cawe-cawe” bukan soal bantu-membantu saja, melainkan permainan catur di mana pion kadang selalu kalah. Dalam permainan ini, yang menang selalu mereka yang memiliki papan catur, bidak, dan bahkan aturan mainnya.
“Cawe-cawe” itu seperti seorang pejabat yang berkata, “Kami hanya ingin membantu stabilitas.”
Tapi stabilitas apa? Stabilitas untuk siapa? Kalau ditanya seperti itu, mereka hanya tersenyum, mungkin sambil melirik rekening bank yang isinya stabil dari tahun ke tahun. Kalau stabilitas berarti memastikan kursi kekuasaan tetap aman untuk golongan tertentu, maka benar, mereka ahli dalam stabilitas. Tapi kalau stabilitas itu berarti membela kepentingan rakyat, maaf, itu urusan lain. Di negeri ini, rakyat diminta memahami bahwa stabilitas adalah ketika mereka tidak banyak bertanya.
Blok Sejarah: Siapa Kawan, Siapa Lawan
Dalam teori Antonio Gramsci, blok sejarah adalah aliansi strategis yang melibatkan kelompok dominan baik politik, ekonomi, maupun budaya yang bekerja bersama untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Blok ini bukan sekadar kerja sama sementara, tetapi sebuah mekanisme sistemik untuk memastikan dominasi tetap terjaga dan kekuatan lawan selalu lemah.
Di Indonesia, blok sejarah bukan sekadar wacana teori; ia adalah kenyataan yang kita saksikan setiap hari. Blok sejarah ini adalah koalisi antara elite politik, pengusaha besar, dan simbol agama atau budaya yang digunakan seperti alat di kotak peralatan perkakas. Ketika elite berkata, “Ini demi bangsa dan negara,” apa yang sebenarnya mereka maksudkan adalah “Ini demi kami dan kepentingan kami.”
Mereka menggunakan narasi yang membius, melukis diri mereka sebagai penyelamat, sementara kekuasaan digenggam erat hanya untuk melanggengkan privilese. Di belakang layar, ini adalah permainan besar, di mana rakyat hanya menjadi pion di atas papan catur.
Lihatlah bagaimana media, yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi, berubah menjadi corong blok sejarah ini. Media digunakan untuk menciptakan narasi stabilitas, kemajuan, dan pembangunan. Mereka mengulang-ulang cerita tentang bahaya keretakan sosial atau ancaman terhadap bangsa untuk membenarkan segala keputusan elite.
Tetapi narasi ini tidak pernah membahas bagaimana koalisi elite, yang melibatkan politisi, pemodal besar, dan simbol agama ternyata mencengkram kekuasaan. Diskusi tentang ketimpangan atau dominasi selalu dibungkam dengan alasan bahwa mengungkit-ungkit hal tersebut dianggap “mengancam stabilitas.”
Di sisi lain, agama dijadikan pelumas untuk melancarkan kekuasaan. Simbol-simbol spiritual digunakan untuk menciptakan kesan bahwa semua kebijakan, meski merugikan rakyat, telah “diberkahi” oleh sesuatu yang lebih tinggi. Ini bukan kebetulan; ini adalah strategi. Narasi ini menguatkan posisi elite dengan mengalihkan fokus rakyat dari kebijakan yang timpang kepada isu moral yang dikemas dengan religiusitas.
Hasilnya? Sebuah legitimasi palsu yang sulit dilawan karena siapa pun yang melawannya akan dianggap tidak menghormati agama. Tidak cukup dengan itu, nasionalisme juga dijadikan tameng untuk melindungi kekuasaan. Narasi nasionalisme sering digunakan untuk membungkam kritik. Rakyat diberi slogan-slogan indah seperti “Demi keutuhan bangsa” atau “Demi stabilitas nasional.”
Tetapi slogan ini sebenarnya hanyalah permen politik untuk membuat rakyat diam, seperti seorang anak kecil yang diberi gula-gula agar tidak rewel. Dengan mengemas setiap kebijakan dalam retorika nasionalisme, elite memanipulasi emosi rakyat untuk menerima dominasi tanpa mempertanyakan siapa yang benar-benar diuntungkan.
Rakyat: Penonton yang Mulai Bosan
Demokrasi seharusnya menjadi panggung di mana rakyat memainkan peran utama. Namun, kenyataan di Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya: rakyat semakin dipinggirkan, menjadi sekadar penonton yang tak lagi antusias terhadap lakon yang terus diulang-ulang. Ketika demokrasi hanya dijalankan sebatas prosedur tanpa makna substantif, ia berubah menjadi hiasan kosmetik megah dari luar, tetapi kosong di dalam.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Eswatini, adalah salah satu negara di Afrika, menggunakan pemilu sebagai alat kosmetik untuk menunjukkan keterlibatan rakyat. Tetapi semua orang tahu, kekuasaan tetap berada di tangan keluarga kerajaan. Rakyat tidak benar-benar memiliki suara, hanya berfungsi sebagai latar belakang dalam pertunjukan kekuasaan yang telah lama diatur.
Indonesia mungkin tidak memiliki monarki absolut, tetapi rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencerminkan masalah yang serupa. Tingkat partisipasi hanya mencapai 68,16%, jauh lebih rendah dibandingkan Pemilu Presiden dan Legislatif yang mencapai 81% (Kompas, 2024). Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah sinyal kelelahan rakyat terhadap proses politik yang mereka rasa tidak memberi pilihan nyata.
Apatisme ini menunjukkan bahwa rakyat semakin skeptis terhadap demokrasi yang hanya melibatkan mereka secara prosedural, tetapi tidak memberikan kontrol atas hasilnya. Demokrasi, dalam kondisi seperti ini, kehilangan daya tariknya karena rakyat merasa hanya dimanfaatkan sebagai legitimasi politik, sementara kekuasaan tetap terpusat di tangan segelintir elite.
Dominasi Dinasti dan Oligarki, Pembunuh Regenerasi Politik
Di banyak negara kecil, dominasi kekuasaan oleh keluarga atau kelompok tertentu menjadi penghalang utama bagi regenerasi politik. Togo, negara kecil di Afrika Barat, telah diperintah oleh dua keluarga besar sejak kemerdekaan. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada oposisi yang benar-benar bisa tumbuh, dan rakyat hanya menjadi penonton dalam skenario yang sudah ditentukan.
Indonesia mengalami masalah serupa. Politik dinasti telah menjadi wajah umum Pilkada, dengan dukungan elite pusat sebagai penguat utama. Kandidat independen hampir tidak memiliki ruang untuk bersaing. Dalam sistem seperti ini, demokrasi kehilangan fungsinya sebagai ruang kompetisi yang sehat dan terbuka. Yang tersisa hanyalah formalitas untuk memberi kesan bahwa rakyat terlibat, padahal keputusan sudah lama dibuat oleh elite.
Jika politik adalah panggung, maka rakyat adalah penonton yang mulai bosan. Mereka duduk diam, menyaksikan drama yang ceritanya mudah ditebak: elite saling rebut kekuasaan, membuat janji kosong, lalu lupa segalanya begitu menang. Pada Pilkada 2024, angka partisipasi pemilih hanya 68,16%. Angka ini sering dipakai pemerintah untuk membanggakan diri “Masih tinggi!” katanya. Tapi siapa yang mereka bodohi? Dalam diam, rakyat sebenarnya ingin berkata, “Untuk apa memilih, kalau hasilnya selalu sama?”
Dan beginilah demokrasi kita. Ia berjalan seperti mobil tua yang knalpotnya bocor. Dari luar terlihat masih berfungsi, tapi penumpangnya sudah pusing oleh asap. Ketika media massa jadi alat propaganda, ketika organisasi masyarakat malah jadi perpanjangan tangan kekuasaan, ketika simbol agama dijadikan senjata untuk membungkam kritik, maka demokrasi bukan lagi milik rakyat. Ia hanya menjadi alat untuk menutupi wajah otoritarianisme yang semakin tua dan berkerut.
Menuju Demokrasi yang Lucu tapi Serius
Mari kita jujur sejenak: apakah rakyat benar-benar diam? Jawabannya, tentu saja, tidak. Rakyat tidak pernah sepenuhnya diam. Di balik wajah apatis yang sering digambarkan dalam narasi elite, sebenarnya ada bentuk resistensi kecil yang terus tumbuh di bawah permukaan. Mereka bicara di media sosial, mendukung kandidat independen, atau bahkan memilih golput sebagai cara untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sistem.
Resistensi ini mungkin tidak terorganisir, tetapi ia cukup untuk membuat elite gelisah. Mereka tahu, di balik kepasifan rakyat, ada potensi besar untuk melawan. Sebuah gerakan yang ketika muncul, bisa mengguncang blok kekuasaan yang telah mapan selama bertahun-tahun. Pada sisi lain, melawan sistem yang telah begitu rapat mengikat bukanlah perkara mudah. Demokrasi di Indonesia seperti perangkap tikus: tampaknya ada celah untuk bergerak, tetapi setiap langkah menghadapi hambatan yang tak terlihat.
Narasi besar yang dikuasai elite, dominasi sistem, dan kontrol atas aparatus negara membuat perjuangan rakyat menjadi semakin sulit. Lalu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Apakah mungkin bagi rakyat untuk melawan sistem yang tampaknya dirancang untuk mempertahankan status quo?
Perlawanan Terorganisir, Harapan Melawan “Cawe-Cawe”
Ada harapan, tentu saja, tetapi itu hanya bisa tercapai jika perlawanan rakyat diorganisir dan diarahkan dengan baik. Sebuah demokrasi tidak bisa tumbuh tanpa tiga elemen utama: institusi yang independen, partisipasi rakyat yang aktif, dan budaya politik yang sehat. Jika salah satu dari elemen ini tidak berfungsi, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung teater, di mana rakyat dipaksa menonton lakon yang mereka tahu akhirnya.
Berikut adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil untuk melawan “cawe-cawe” yang telah melumpuhkan demokrasi Indonesia:
- Independensi Lembaga Demokrasi
Lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP seharusnya menjadi penjaga netralitas demokrasi. Ternyata, dalam banyak kasus, mereka sering kali terjebak dalam pusaran kekuasaan elite. Kecurigaan publik terhadap independensi lembaga-lembaga ini bukanlah isapan jempol. Banyak keputusan yang terlihat lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan elite daripada menjaga integritas pemilu.
Langkah pertama untuk melawan “cawe-cawe” adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga ini benar-benar bebas dari tekanan politik. Bukan sekadar reformasi plasebo, tetapi restrukturisasi menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka bekerja hanya untuk rakyat, bukan menjadi stempel kekuasaan elite. Jika lembaga pengawas demokrasi tidak dapat dipercaya, maka seluruh proses politik akan terus diragukan.
- Transparansi Pendanaan Politik
Salah satu akar masalah dalam demokrasi Indonesia adalah politik uang. Pemilu sering kali dimenangkan bukan oleh kandidat terbaik, tetapi oleh mereka yang memiliki modal paling besar. Uang menjadi senjata utama untuk membeli suara, media, bahkan lembaga negara. Dalam sistem seperti ini, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa suara mereka memiliki arti?
Transparansi pendanaan politik harus menjadi prioritas utama. Semua sumber dana kampanye, baik di tingkat lokal maupun nasional, harus dilaporkan secara terbuka dan diaudit oleh lembaga independen. Selain itu, aturan tentang batas pengeluaran kampanye harus ditegakkan secara ketat, dan hukuman bagi pelanggaran harus lebih berat. Jika uang terus menjadi pengendali utama politik, maka demokrasi Indonesia tidak akan pernah benar-benar bebas.
- Hentikan Mobilisasi Aparatur Negara
Mobilisasi aparatur negara untuk mendukung kandidat tertentu adalah bentuk “cawe-cawe” yang paling mencolok. Pegawai negeri sipil, militer, dan polisi sering kali dimanfaatkan untuk mendukung agenda politik elite, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, banyak laporan tentang netralitas ASN yang dilanggar selama pemilu menunjukkan bahwa aparatur negara telah menjadi alat politik daripada pelayan rakyat.
Netralitas aparatur negara harus dijaga dengan ketat. Keterlibatan mereka dalam politik praktis bukan hanya merusak demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Pelanggaran netralitas harus dihukum tegas, dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan melibatkan masyarakat sipil.
- Pendidikan Politik Sejak Dini
Demokrasi bukan hanya tentang memilih bupati, gubernur, atau presiden. Ia adalah sistem di mana rakyat menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka. Tetapi, di Indonesia, demokrasi sering kali direduksi menjadi sekadar aktivitas lima tahunan, di mana rakyat diminta datang ke TPS, memilih, dan pulang tanpa benar-benar memahami apa yang mereka pilih.
Pendidikan politik harus diberikan sejak dini, tidak hanya di sekolah, tetapi juga melalui program masyarakat. Rakyat harus diajarkan bahwa demokrasi adalah hak yang harus diperjuangkan, bukan sekadar rutinitas. Mereka harus memahami bahwa suara mereka adalah kekuatan nyata yang bisa mengubah sistem, asalkan mereka mau menggunakannya dengan bijak.
Pendidikan politik juga harus mencakup etika politik, sesuatu yang sering diabaikan dalam diskursus demokrasi Indonesia. Jika generasi muda tidak diajarkan tentang nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan, maka mereka akan tumbuh menjadi pengikut sistem yang korup, bukannya pembaru.
Memang Rakyat Adalah Kuncinya Pada akhirnya, semua langkah ini tidak akan berarti apa-apa tanpa partisipasi aktif dari rakyat. Jika rakyat hanya diam dan menerima, elite akan terus bermain dengan aturan yang mereka buat sendiri. Mereka akan terus menciptakan narasi bahwa stabilitas lebih penting daripada keadilan, bahwa konsensus lebih penting daripada kebebasan.
Tetapi ketika rakyat mulai bergerak, segalanya bisa berubah. Resistensi kecil seperti yang terlihat di media sosial, dukungan terhadap kandidat independen, dan bahkan aksi golput adalah tanda-tanda bahwa rakyat tidak benar-benar pasif. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk bersuara lebih lantang.
Hanya saja, perlawanan rakyat harus diarahkan. Mereka tidak boleh hanya menjadi reaksi terhadap kebijakan buruk, tetapi menjadi gerakan yang konsisten menuntut perubahan. Jika perlawanan ini bisa terorganisir, maka “cawe-cawe” elite tidak lagi tak terkalahkan.
Akhir Sebuah Drama, atau Awal Baru?
“Cawe-cawe” adalah cermin buruk dari politik kita, sebuah gambaran getir tentang bagaimana demokrasi yang seharusnya menjadi milik rakyat kini berubah menjadi permainan elite yang merugikan. Mereka yang berada di puncak panggung menikmati lakon ini dengan senyum lebar, sementara mereka yang berada di bawah hanya bisa menonton dengan gundah.
Demokrasi, ruang yang seharusnya penuh dengan suara rakyat, kini tak lebih dari ruang tunggu tanpa kepastian. Kita menunggu bukan untuk perubahan yang lebih baik, tetapi untuk kejatuhan yang mungkin akan lebih dalam.
Sebaliknya, seperti kehidupan, politik selalu penuh dengan kemungkinan. Tidak ada sistem yang begitu sempurna sehingga tidak bisa digoyahkan, dan tidak ada kekuasaan yang begitu kokoh sehingga abadi. Dalam absurditas “cawe-cawe,” di mana elite memaksakan narasi tentang stabilitas, loyalitas, dan kekuasaan, terdapat ruang kecil untuk melawan.
Ruang ini adalah harapan, sebuah celah sempit yang hanya bisa direnggangkan jika rakyat mulai berdiri dan bersuara. Seperti dalam semua drama yang membosankan, penonton hanya bisa bertahan untuk waktu tertentu.
Siapa yang terus bertepuk tangan pada cerita buruk? Lambat laun, mereka akan berdiri, menuntut cerita yang baru, pemeran yang berbeda, dan naskah yang lebih menggugah. Dan pada saat itu, elite hanya punya dua pilihan: berubah untuk memenuhi tuntutan rakyat, atau disingkirkan oleh sejarah yang lebih besar dari mereka. (*)