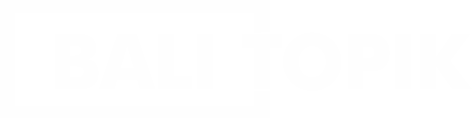Oleh: Filemon Bram Gunas Junior (Ketua Presidium PMKRI Denpasar)
OPINI- Bali, dalam diskursus global, sering kali dipuja sebagai laboratorium harmoni yang inklusif. Namun, di balik narasi estetika pariwisatanya, dinamika urban di Pulau Dewata kini sedang menghadapi ujian serius berupa “Dilema Ruang dan Identitas”.
Fenomena segregasi hunian di mana akses terhadap ruang (kos-kosan) mulai terdistorsi oleh filter identitas kedaerahan tertentu menjadi sinyal adanya polusi sosial yang mengancam struktur solidaritas kebangsaan kita.
Secara sosiologis, apa yang dialami oleh mahasiswa dan warga perantau asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Bali belakangan ini adalah bentuk nyata dari labeling theory. Tindakan deviatif atau pelanggaran norma yang dilakukan oleh segelintir oknum telah mengalami eskalasi menjadi stigma kolektif. Terjadi kegagalan logika sistemik di mana “dosa” individu ditransformasikan menjadi beban identitas suku.
Dalam kacamata ekologi sosial, stabilitas sebuah kawasan bergantung pada interaksi yang sehat antar-elemen penyusunnya. Masyarakat perantau bukan sekadar entitas asing, melainkan bagian integral dari metabolisme ekonomi dan intelektual Bali. Ketika hak atas ruang hunian dipangkas hanya berdasarkan asal geografis, kita sebenarnya sedang membangun tembok eksklusi yang mencederai prinsip keberagaman.
Eksklusi Spasial sebagai Polusi Sosial Sebagai mahasiswa, saya memandang masalah ini tidak hanya sebagai isu moral, tetapi sebagai kegagalan manajemen sosial di ruang urban. Eksklusi spasial yakni kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal menciptakan rasa keterasingan (alienation) yang mendalam. Ruang hunian seharusnya menjadi tempat pertama di mana integrasi sosial terjadi, bukan justru menjadi garis depan diskriminasi primordial.
Jika praktik “pintu tertutup” ini dinormalisasi, maka visi Indonesia Emas yang kita cita-citakan akan rapuh di level akarnya. Solidaritas kebangsaan tidak boleh kalah oleh rasa takut yang irasional.
Penegakan hukum (law enforcement) yang tegas terhadap setiap pelanggar hukum, tanpa memandang latar belakangnya, adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional, bukan dengan melakukan penghakiman masal terhadap kelompok identitas tertentu.
Restorasi Solidaritas Sebagai bagian dari elemen organisasi mahasiswa, kami menyadari bahwa harmoni menuntut tanggung jawab dua arah. Prinsip “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” adalah komitmen mutlak para perantau untuk beradaptasi dengan kearifan lokal Bali (Desa Kala Patra). Namun, adaptasi tersebut membutuhkan ruang yang adil dan kesempatan yang setara.
Diperlukan dekonstruksi terhadap stigma melalui dialog yang berbasis data dan kemanusiaan. Tokoh adat, akademisi, dan pemimpin organisasi harus duduk bersama untuk meredam residu konflik yang ada. Bali harus tetap menjadi rumah bagi semua anak bangsa yang ingin belajar dan berkarya.
Konklusi Menakar ulang solidaritas kebangsaan berarti berani menolak segala bentuk prasangka yang memecah belah. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan identitas menjadi penghalang bagi hak-hak dasar manusia. Mari kita pulihkan kembali wajah Bali yang inklusif, demi merawat Indonesia yang satu. (*)