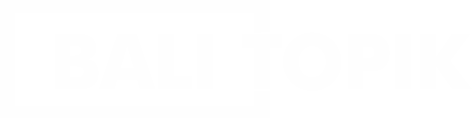Penulis: Yoh. Sandriano N. Hitang – Mahasiswa Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung
Penggagas Forum Intelektual Peduli Demokrasi dan Kebijakan Publik (FORMASI-KP)
OPINI – Akhir Agustus 2025 akan tercatat sebagai masa ketika jalan raya menjadi ruang tafsir baru tentang negara. Bukan sekadar aspal dan beton, melainkan panggung di mana suara publik bertemu dengan kebuntuan kekuasaan.
Di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, hingga Makasar, demonstrasi menggulung bagai gelombang pasang. Jalanan kota-kota besar itu menjadi saksi ledakan kemarahan publik. Demonstrasi yang kian meluas ini menandai eskalasi ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik. Pemicunya beragam. Mulai dari penolakan terhadap tunjangan perumahan DPR yang dinilai fantastis, hingga tragedi kematian Affan yang ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob.
Tentu, ada yang menyebut demonstrasi itu sebagai akumulasi kekecewan publik. Tidak salah. Akan tetapi, lebih tepat kita menyebutnya sebagai ekspresi kegelisahan moral. Situasi ini mudah untuk ditemukan. Dalam pekik mahasiswa, orasi buruh, solidaritas gerakan ojol, hingga pedagang kaki lima, ada satu kata kunci yang menyatukan: ketidakadilan.
Mereka marah bukan semata karena uang negara yang dijarah atau hak kolektif yang dirampas, tetapi juga karena merasa ditinggalkan oleh sebuah janji: janji bahwa negara hadir untuk berlaku adil, mengayomi, melindungi, bukan sekadar memerintah atau menggenggam kekuasaan. Dan dari sekian tuntutan, satu suara terdengar paling nyaring: “Sahkan RUU Perampasan Aset!”
RUU ini, yang telah bertahun-tahun tidur di meja DPR, kini menjadi simbol perlawanan publik terhadap oligarki sekaligus simbol kerinduan akan negara yang berpihak pada warganya. Publik tak lagi sekadar berdiam diri, mereka tampil dengan gerakan yang masif, menuntut keberpihakan yang nyata.
Antara Negara dan Kekuasaan yang Tersandera
Tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sejatinya membuka tabir persoalan yang lebih mendasar. Di balik pekik demonstrasi dan desakan publik, tersimpan keresahan yang jauh lebih dalam: kegagalan negara dalam menjaga kontrak sosial dan kecenderungannya untuk tersandera oleh kepentingan elite.
Kita sering lupa bahwa korupsi bukan hanya kejahatan finansial; ia adalah pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Dalam kontrak sosial, rakyat memberikan mandat politiknya kepada negara, agar negara sebagai agen mengatur kepentingan bersama. Jika akhirnya korupsi merajalela, maka kerugian negara akibat korupsi adalah luka yang meluluhlantakkan legitimasi moral dan politik. Tidak berlebihan bila rakyat akhirnya merasa dikhianati, dan negara kehilangan otoritas etis untuk memerintah.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara yang telah inkrah akibat kasus korupsi sepanjang 2014-2022 mencapai Rp234,68 triliun (CNBC,18/8/2024). Jumlah ini tentu fantastis. Tetapi angka itu hanyalah gejala. Luka yang sesungguhnya lebih dalam adalah hilangnya kepercayaan pada negara.
Di balik lambannya pembahasan RUU Perampasan Aset, kita membaca satu hal yang lebih menakutkan daripada korupsi itu sendiri: politik yang tersandera oleh kepentingan elite. Banyak yang gamang jika aturan ini disahkan, takut pada bayang-bayang kemungkinan yang akan muncul pasca RUU ini disahkan.
Pada titik ini, parlemen kehilangan daya sebagai representasi rakyat. Kita seolah menyaksikan Senayan sebagai cermin buram demokrasi, tempat suara publik diredam dan kepentingan segelintir orang dirawat. Wajar jika sebagian publik mulai memalingkan harapannya ke satu figur yang dianggap masih punya ruang manuver: Presiden.
Janji Istana, Jalan Perppu, dan Ujian Keberanian Politik
Di tengah gelombang demonstrasi dan desakan publik yang kian meluas, kabar dari Istana sebagaimana dilansir dari Kompas.com, mencuri perhatian. Presiden Prabowo, dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, dan serikat buruh pada 1 September 2025, berjanji bahwa RUU Perampasan Aset akan segera dibahas. Janji itu tentu menyalakan secercah harapan, setidaknya publik merasa suaranya tersampaikan ke pusat kekuasaan.
Namun, sejarah politik kita mengajarkan bahwa janji selalu berada di ruang antara harapan dan keraguan, antara kemungkinan dan ketidakpastian. Ia bisa ditepati, tetapi tak jarang pula menjadi sekadar retorika yang larut dalam kalkulasi politik. Janji memang menyalakan harapan, tetapi juga menyimpan bayang-bayang pengingkaran.
Di sinilah pertaruhan moral seorang pemimpin diuji. Bila janji itu diingkari, maka negara tidak hanya kehilangan kepercayaan, melainkan juga meneguhkan citra sebagai entitas yang lebih pandai merawat kata daripada menunaikan makna. Karena itu, yang ditunggu bukan hanya janji, melainkan keberanian mengambil keputusan yang berani.
Dalam kondisi ini, Perppu Perampasan Aset hadir sebagai jalan yang lebih tegas. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 membuka jalan itu: Presiden memiliki hak prerogatif untuk menerbitkan Perppu dalam kondisi “kegentingan yang memaksa.” Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan No.138/PUU-VII/2009, menetapkan tiga syarat utama: singkatnya, ada kebutuhan mendesak, aturan yang ada tak memadai, dan kebuntuan legislasi.
Tentu, para punggawa hukum di negeri ini bisa punya seribu satu macam alasan untuk mendukung ataupun menolak gagasan ini. Tetapi, lihatlah kondisi kita sekarang: protes sosial merebak, DPR gagal memberi jawaban, dan kerugian negara terus bertambah. Belum lagi polarisasi yang menjalar ke mana-mana dengan ruang digital yang semakin memperuncing fragmentasi wacana. Tiga syarat kegentingan yang memaksa itu jelas terpenuhi. Maka, menerbitkan Perppu Perampasan Aset bukan sekadar sah secara konstitusional, melainkan juga sebuah ujian keberanian politik.
Hanya saja, keberanian politik selalu diuji di persimpangan sejarah: apakah Presiden memilih jalan kompromi, atau berdiri tegak di sisi publik yang resah? Ini bukan lagi soal prosedur hukum, tetapi pesan moral tentang keberpihakan.
Masyarakat yang Letih Menunggu
Apa yang tampak dalam demonstrasi di awal tulisan ini pada akhirnya bermuara pada kenyataan yang lebih sunyi: masyarakat yang terus menunggu tanpa kepastian. Sebab, di balik setiap teriakan demonstrasi, ada wajah-wajah letih yang tak selalu tampak di layar media. Para petani yang sawahnya tak bisa ditanami karena irigasi rusak, para buruh yang gajinya tak sebanding dengan kebutuhan pokok, para mahasiswa yang terpaksa cuti karena biaya kuliah terlanjur mahal, tetapi tak ada yang benar-benar tahu kapan janji perubahan itu tiba.
Bagi mereka, korupsi bukan sekadar istilah dalam laporan tahunan lembaga negara atau angka statistik yang dingin. Korupsi adalah hilangnya pupuk bersubsidi, jalan desa yang tak pernah selesai diperbaiki, biaya rumah sakit yang tak sanggup mereka bayar, dan uang kuliah yang sulit dijangkau. Sementara di sisi lain, para koruptor hidup tenang, menikmati hasil kejahatan tanpa malu, seolah hukum adalah ruang yang bisa dinegosiasikan.
Maka, Perppu Perampasan Aset bukan hanya soal memulihkan uang negara; ia adalah penegasan moral bahwa negara tidak boleh tunduk pada permainan segelintir elit. Perppu itu adalah pengingat bahwa kedaulatan rakyat hanya bermakna jika negara berani mengembalikan apa yang telah dirampas dari mereka yang paling berhak: rakyat kecil yang selama ini diam, letih, dan hanya bisa menunggu.
Radical Reform: Membuka Jalan Baru
Akhirnya, reformasi adalah pertemuan antara keberanian moral dan visi kebangsaan. Hari ini, kalimat itu terasa relevan kembali.
Menerbitkan regulasi tentang perampasan aset boleh jadi bagian dari radical reform yang sudah lama tertunda. Paradigma lama yang menjerat pelaku tetapi membiarkan harta hasil kejahatan tetap dinikmati harus diubah. Jika ingin memulihkan martabat bangsa, kita harus berani memiskinkan koruptor, bukan hanya memenjarakannya.
Di sinilah Presiden diuji, bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai penafsir sejarah bangsanya sendiri. Apakah ia ingin dikenang sebagai pemimpin yang memilih jalan aman, atau sebagai pemimpin yang melompat melawan arus?
Sejarah tidak pernah menunggu pemimpin yang ragu. Saat publik kehilangan kesabaran, waktu berubah menjadi lawan. Mengeluarkan Perppu Perampasan Aset bukan hanya soal hukum, melainkan simbol keberanian moral. Simbol bahwa negara masih berpihak pada rakyatnya, dan kekuasaan bukan sekadar alat melayani elite.
Jika Presiden memilih jalan Perppu, ia tak hanya memulihkan legitimasi pemerintahannya, tetapi juga menulis satu babak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Tetapi jika RUU Perampasan Aset tetap dibahas melalui jalur normal tanpa Perppu, maka prosesnya akan berjalan lebih panjang dan berliku.
Memang, legitimasi politiknya lebih formal karena melalui persetujuan DPR, tetapi risikonya besar: tarik-menarik kepentingan bisa melemahkan substansi, momentum publik yang sedang mendesak bisa terlewat, dan implementasi hukum akan tertunda. Pada akhirnya, publik akan menilai bukan hanya hasil, melainkan kecepatan dan ketegasan negara dalam merespons kegentingan korupsi. (*)