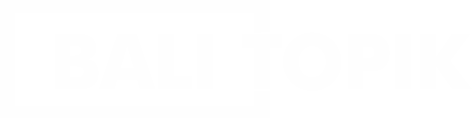Balitopik.com – Delapan dekade sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia berdiri sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, kekayaan alam yang melimpah, serta posisi strategis secara geopolitik. Namun di balik kebanggaan simbolik ini, ada pertanyaan menyakitkan yang harus diajukan dengan jujur dan tanpa euforia nasionalisme semu: Apakah Indonesia benar-benar telah merdeka dalam arti yang sesungguhnya?
Jika kita ukur kemerdekaan bukan sekadar dari bebasnya kita dari penjajahan kolonial, tapi juga dari terpenuhinya janji-janji kemerdekaan itu sendiri, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, kedaulatan bangsa, dan tegaknya demokrasi, maka jawabannya belum. Dan belum itu bukan karena kita gagal bermimpi besar, tetapi karena kita terlalu lama berpuas diri pada simbol-simbol tanpa menggali substansi.
Kemandirian yang Masih Sekadar Mimpi
Delapan puluh tahun berjalan, Indonesia belum mampu keluar dari mentalitas ketergantungan. Dalam ekonomi, negara ini masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Industri hilir tidak berkembang secara mandiri karena kebijakan yang inkonsisten, korupsi struktural, serta tekanan dari kepentingan asing yang terus menancapkan pengaruhnya dalam bentuk investasi dan utang luar negeri.
Kemandirian energi, pangan, dan teknologi masih jauh dari harapan. Ketika dunia berbicara soal kecerdasan buatan, energi bersih, dan ekonomi digital, Indonesia masih berkutat dengan infrastruktur dasar yang belum merata, serta pendidikan yang tertinggal. Sebagian besar kebijakan justru berorientasi pada keuntungan jangka pendek, bukan pembangunan jangka panjang.
Oligarki: Penjajahan Gaya Baru
Jika dulu penjajah datang dengan senjata dan kekuasaan teritorial, maka hari ini Indonesia dijajah oleh oligarki — sekelompok kecil elite politik dan pengusaha yang mengendalikan sumber daya, kebijakan publik, bahkan narasi media. Demokrasi prosedural berjalan, pemilu diselenggarakan, tapi substansinya mati perlahan.
Partai politik tidak lagi menjadi kendaraan ideologis, melainkan alat transaksi kekuasaan. Jabatan dibeli, bukan didedikasikan. Kebijakan berpihak bukan pada rakyat, tetapi pada pemilik modal yang menyumbang logistik kampanye. Ironisnya, semua ini terjadi dalam sistem yang secara formal disebut demokrasi.
Rakyat Masih Jauh dari Kesejahteraan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — janji luhur yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 — masih menjadi utopia. Ketimpangan ekonomi makin tajam: segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara jutaan rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Buruh diupah rendah, petani dimiskinkan sistem, nelayan dipinggirkan oleh proyek-proyek pesisir yang “berpihak pada pembangunan”.
Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas masih sangat ditentukan oleh status ekonomi. Di tengah gemuruh pembangunan kota, desa-desa dan wilayah terpencil masih dilupakan. Indonesia bukan hanya terbelah secara geografis, tapi juga secara ekonomi dan sosial.
Pendidikan yang Membentuk Generasi Pasrah
Salah satu kegagalan terbesar negara ini adalah pada sistem pendidikannya. Alih-alih membentuk generasi yang kritis, mandiri, dan visioner, sistem pendidikan nasional masih terlalu birokratis, menekankan hafalan, dan minim pemupukan karakter. Sekolah-sekolah sering kali hanya menjadi tempat pelatihan untuk ujian, bukan laboratorium ide dan kemanusiaan.
Tak heran jika lahir generasi yang mudah dipecah oleh sentimen identitas, alergi terhadap perbedaan pendapat, dan lebih sibuk menciptakan pencitraan di media sosial ketimbang membangun gagasan untuk bangsa. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang berani dan benar-benar peduli.
Nasionalisme yang Dikooptasi oleh Kepentingan
Nasionalisme hari ini lebih banyak dikemas dalam seremoni dan jargon. Lagu dinyanyikan, bendera dikibarkan, tetapi di saat yang sama tanah rakyat dirampas atas nama proyek strategis nasional. Mereka yang mempertanyakan kebijakan negara dicap tidak cinta tanah air. Ironisnya, nasionalisme justru dijadikan alat represi oleh kekuasaan yang anti-kritik.
Apa gunanya mencintai negara jika negara tidak mencintai rakyatnya kembali? Apa artinya membela tanah air jika tanah dan air itu sendiri dikuasai korporasi?
Kedaulatan Hukum yang Dilecehkan Kekuasaan
Hukum seharusnya menjadi panglima, tetapi di Indonesia, hukum tunduk pada kekuasaan dan uang. Penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lembaga-lembaga penegak hukum sering kali menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat. Kasus korupsi ditangani setengah hati, sementara aktivis dan pembela rakyat sering dikriminalisasi.
Kita hidup dalam negara hukum, tetapi kenyataannya banyak warga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Keadilan masih menjadi hak istimewa, bukan hak semua orang.
Indonesia memang sudah merdeka dari penjajah asing, tetapi belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan bentuk baru: keserakahan elite, kebodohan sistemik, dan kemiskinan struktural. Merdeka bukan hanya soal berdiri sendiri secara politik, tetapi juga berdaulat dalam ekonomi, berkeadilan dalam sosial, dan beradab dalam budaya.
80 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momen reflektif, bukan sekadar perayaan. Bangsa ini harus berani mengakui kegagalannya agar bisa memperbaiki. Kita tidak kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan kepemimpinan yang jujur, berani, dan visioner.
Jika ingin menjadi bangsa besar, Indonesia harus berhenti berpuas diri pada masa lalu dan mulai bekerja keras untuk masa depan. Merdeka bukan akhir — ia adalah awal dari perjuangan yang terus-menerus. Dan perjuangan itu belum selesai. (*)
TENTANG PENULIS
Nama: Filemon Bram Gunas Junior (Ketua Presidium PMKRI Cabang Denpasar Sanctus Paulus Periode 2025-2026)