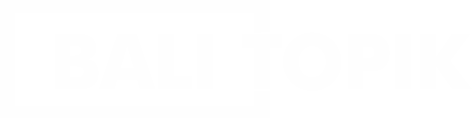Penulis: Kosmas Mus Guntur. Penulis adalah Praktisi Hukum pada kantor Hukum EMG LAW OFFICES di Jakarta dan Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI) Periode 2022-2024.
Balitopik.com, JAKARTA – Unjuk rasa merupakan salah satu ekspresi paling nyata dari demokrasi. Ia menjadi medium bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan kemarahan terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak adil. Dalam sejarah Indonesia, demonstrasi bukan sekadar alat politik, melainkan juga katalis perubahan, dari era pergerakan nasional hingga reformasi 1998. Karena itu, setiap regulasi yang menyentuh hak berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum hampir selalu memicu perdebatan publik.
Polemik serupa kembali mengemuka menjelang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026. Salah satu pasal yang menuai sorotan adalah Pasal 256 KUHP, yang mengatur kewajiban pemberitahuan kepada aparat penegak hukum sebelum pelaksanaan unjuk rasa. Meski pemerintah menegaskan bahwa ketentuan ini bukan bentuk perizinan, sebagian kalangan menilainya sebagai langkah mundur dalam perlindungan kebebasan berpendapat.
Pertanyaannya kemudian: apakah Pasal 256 KUHP benar-benar dimaksudkan untuk menertibkan ruang publik, atau justru berpotensi menjerat para demonstran?
Pasal 256 KUHP pada dasarnya mengatur kewajiban pemberitahuan kepada aparat berwenang sebelum dilaksanakannya unjuk rasa di ruang publik. Norma ini disertai ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda bagi pihak yang tidak melakukan pemberitahuan dan pelaksanaan unjuk rasanya menimbulkan gangguan kepentingan umum atau huru-hara.
Penting dicatat, unsur pemidanaan dalam pasal ini bersifat kumulatif. Artinya, tidak setiap demonstrasi tanpa pemberitahuan otomatis dipidana. Ancaman pidana baru berlaku apabila ketiadaan pemberitahuan tersebut berujung pada gangguan ketertiban umum. Sebaliknya, bagi demonstrasi yang telah melakukan pemberitahuan dan berlangsung tertib, ketentuan pidana ini tidak berlaku.
Di atas kertas, konstruksi pasal ini tampak moderat. Ia tidak melarang demonstrasi, tidak mensyaratkan izin, dan tidak menutup ruang kritik. Namun, sebagaimana banyak regulasi hukum pidana lainnya, persoalan utama tidak berhenti pada bunyi norma, melainkan pada tafsir dan praktik penegakannya.
Pemerintah, melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Eddy O.S. Hiariej, menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Menurutnya, pasal ini justru bertujuan menciptakan keteraturan dalam penggunaan ruang publik agar hak satu kelompok tidak mengorbankan hak kelompok lainnya.
Dalam pandangan pembentuk undang-undang, kewajiban pemberitahuan diperlukan agar aparat dapat melakukan pengamanan, rekayasa lalu lintas, dan mitigasi risiko konflik. Dengan demikian, demonstrasi dapat berlangsung aman, baik bagi peserta aksi maupun masyarakat luas. Pemerintah juga menekankan bahwa pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi demonstran yang telah bertindak sesuai prosedur.
Argumen ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip negara hukum modern, di mana kebebasan tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan hak orang lain. Demokrasi, dalam kerangka ini, bukan sekadar kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.
Kekhawatiran Masyarakat
Meski demikian, kritik dari masyarakat sipil tidak bisa diabaikan. Kekhawatiran utama terletak pada potensi multitafsir, khususnya terkait frasa “gangguan kepentingan umum” dan “huru-hara”. Istilah-istilah ini memiliki ruang interpretasi yang luas dan rawan digunakan secara subjektif oleh aparat di lapangan.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa regulasi yang secara normatif tampak netral dapat berubah menjadi instrumen represif ketika berhadapan dengan kritik terhadap kekuasaan. Demonstrasi spontan, misalnya sebagai respons atas kebijakan mendadak atau peristiwa darurat, juga berpotensi dikriminalisasi karena tidak memenuhi syarat pemberitahuan, meskipun esensinya merupakan ekspresi politik yang sah.
Kekhawatiran lainnya adalah pergeseran makna pemberitahuan menjadi izin secara faktual. Dalam praktik, garis pemisah antara “memberi tahu” dan “meminta izin” sering kali kabur. Jika aparat memiliki kewenangan luas untuk menilai apakah sebuah aksi berpotensi mengganggu ketertiban umum, maka ruang diskresi yang besar ini dapat menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam konteks ini, pertanyaan “menjerat atau menertibkan” sesungguhnya tidak dapat dijawab secara hitam-putih. Secara normatif, Pasal 256 KUHP tidak secara eksplisit mengekang kebebasan berpendapat. Ia bahkan dapat dibaca sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan unjuk rasa.
Namun, hukum pidana bekerja bukan hanya melalui teks, melainkan juga melalui aparat penegak hukum dan kultur institusionalnya. Tanpa pedoman teknis yang jelas, pelatihan aparat yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang efektif, pasal ini berpotensi menjadi alat kriminalisasi selektif.
Dalam negara demokrasi, pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Artinya, pembatasan hanya boleh dilakukan sejauh benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan. Jika penerapan Pasal 256 justru menimbulkan efek jera (chilling effect) bagi warga untuk menyampaikan pendapat, maka tujuan demokrasi itu sendiri menjadi tereduksi.
Menurut hemat penulis, Alih-alih terjebak pada dikotomi pro dan kontra, perdebatan mengenai Pasal 256 KUHP seharusnya diarahkan pada upaya mencari jalan tengah. Pertama, pemerintah perlu memastikan adanya aturan pelaksana yang rinci dan transparan, terutama mengenai indikator “gangguan ketertiban umum”.
Kedua, aparat penegak hukum harus didorong untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan represif. Demonstrasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan ancaman keamanan semata. Ketiga, masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan pasal ini. Pengawasan publik yang kuat akan menjadi penyeimbang terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.
Pada prinsipnya, Pasal 256 KUHP tidak dapat dilepaskan dari konteks demokrasi Indonesia yang masih terus berproses. Ia bisa menjadi instrumen penataan ruang publik yang adil, atau sebaliknya, menjadi simbol kemunduran kebebasan sipil, semuanya bergantung pada cara negara menafsirkan dan menerapkannya.
Demokrasi tidak diukur dari ketiadaan aturan, melainkan dari keberanian negara untuk melindungi kritik warganya. Jika Pasal 256 KUHP dijalankan dengan semangat tersebut, maka ia tidak akan menjerat demonstran, melainkan justru menguatkan demokrasi yang tertib dan berkeadaban. (*)