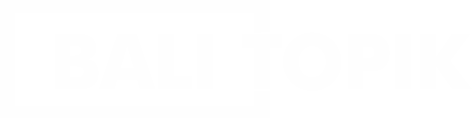Penulis: Robertus Dicky Armando – Akademisi
OPINI – Peristiwa sejarah 1998 kiranya akan terulang kembali. Kali ini pemicu demonstran datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang konon katanya sebagai wakil rakyat, yang akhir-akhir ini bisa berubah menjadi Dewan Penghianat Rakyat (DPR).
Gerakan aksi massa dari semua penjuru mulai dilakukan hingga saat ini. Demo besar-besaran terjadi bukan tanpa sebab. Kekecewaan rakyat terhadap lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, namun semakin hari justru tampak lebih sibuk mengurus kepentingan dirinya sendiri.
Banyak kebijakan yang dikeluarkan DPR justru berdampak negatif bagi masyarakat mulai dari kebijakan kenaikan gaji DPR, tingginya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, minimnya transparansi dalam proses legislasi dan lahirnya undang-undang yang sering kali kontroversial memperburuk citra lembaga ini.
Bahkan, dalam situasi ekonomi rakyat yang sulit, ketika harga-harga kebutuhan pokok terus melambung dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor, publik justru dikejutkan oleh kabar usulan kenaikan tunjangan DPR hingga Rp 50 juta per bulan. Keputusan yang terasa ironis, ketika rakyat diminta berhemat, wakil rakyat justru menambah kenyamanan hidupnya.
Akumulasi kekecewaan inilah yang kemudian menjadi pemicu wacana “Pembubaran DPR”. Wacana kembali menyeruak di tengah publik. Indonesia sebagai negara hukum sudah pasti semua praktek politik diatur di dalam konstitusi. Begitu juga tentang wacana pembubaran DPR. Apabila hukum adalah panglima tertinggi, maka siapakah rajanya?
Sejarah pernah mencatat pembubaran DPR pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Namun, situasi kini berbeda. Setelah empat kali amandemen UUD 1945, posisi DPR semakin kokoh dalam sistem ketatanegaraan kita. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, artinya semua tindakan harus melalui jalur hukum.
Lebih tegas lagi, Pasal 7c menyebutkan bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan dewan perwakilan rakyat.” Artinya, secara konstitusional, DPR kini kebal dari intervensi presiden.
Secara teoritis, dalam sistem presidensial, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen, begitu pula sebaliknya. Kekuatan utama dalam konsep sistem presidensial memang terletak pada prinsip pokok tersebut, terciptanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
Hal ini seperti yang tertuang dalam bingkai teori politik Montesquieu tentang Trias Politica, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut.
DPR sebagai cabang legislatif memiliki kedudukan setara dengan presiden, bukan di bawah presiden. Dengan demikian, jalan pembubaran DPR oleh Presiden seperti era Soekarno atau Gus Dur kini sudah tertutup.
Jika demikian seperti itu, lantas jalur apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil?
Secara hukum dan politik bisa dilakukan dengan melalui amandemen UUD 1945. Hal ini bisa membuka peluang untuk pembubaran DPR. Sehingga salah satu tuntutan massa aksi adalah mendorong perubahan tersebut agar segera dilakukan.
Ini bisa menjadi pembaharuan hukum dan politik untuk kedepannya. Sehingga DPR tidak menjadi lembaga yang Superbody. Akan tetapi hal ini akan menjadi tantangan karena akan melibatkan anggota DPR itu sendiri, yang mungkin sebagian besar ada yang setuju dan ada yang tidak.
Seara sosial dan politik, jika DPR kehilangan legitimasi dari rakyat, masyarakat sipil bisa gunakan prinsip Vox Populi Vox Dei ( Suara rakyat adalah suara Tuhan) yang menjadi dasar moral yang mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan dan kedaulatan tertinggi sejatinya berasal dari rakyat. Sehingga, parlemen jalanan menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan adanya perubahan total.
Parlemen jalanan yang kini menjadi salah satu alternatif apabila usul dan masukan ditolak dan dibungkam. Sidang rakyat menjadi alternatif terakhir.
Kendati, pembubaran DPR menggunakan pendekatan politik, hukum, dan sosial tidak dapat dilakukan, masyarakat bisa melibatkan kalangan akademisi dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan kajian setiap kebijakan yang dikeluarkan, yang kemudian mengirimkan perwakilan-perwakilan dari setiap daerah yang terdiri perwakilan buruh, petani, nelayan, dan pihak terkait untuk berdialog secara terbuka bersama dengan DPR dan membuat sebuah perjanjian antara Anggota DPR dan masyarakat. Sehingga ini menjadi dasar hukum untuk mempersoalkan DPR selama masa jabatannya jika tidak berpihak pada rakyat.
Tragedi Kemanusian
Demo masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR kini berubah menjadi sebuah “Tragedi Kemanusian”. DPR yang seharusnya menyambut baik masa aksi malah menggunakan aparat kepolisian sebagai garda terdepan untuk berhadapan dengan massa aksi. Alhasil seorang pengemudi ojek online grab tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) barracuda Brimob Polda Metro Jaya ketika demo menuntut pembubaran dpr yang berakhir ricuh, kamis, 28 Agustus 2025.
Tragedi ini menjadi semakin membuat masyarakat semakin geram dan kecewa. Hal ini justru membuat semakin banyak demonstran di setiap daerah. Dalam fenomena ini membuat kepolisian juga semakin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Polisi yang seharusnya mengayomi tapi justru menjadi alat penindas yang dikerahkan oleh kekuasaaan.
Situasi saat ini sepertinya sudah berubah. Sepertinya ada pengalihan isu yang dilakukan, yang awalnya membubarkan DPR karena kebijakannya, tapi sekarang justru seperti dialihkan kepada kepolisian karena adanya tragedi kemanusian.
Seolah –olah saat ini para anggota DPR sedang menonton peristiwa masyarakat dan polisi yang juga menjadi bagian dari dampak kebijakan yang dikeluarkan DPR.
Dalam pertanggungjawaban dihadapan hukum, oknum-oknum polisi tersebut tetap diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Keluarga korban dan masyarakat menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum itu adalah yang wajar. Sekiranya patut dikatakan, bahwa tragedi ini juga menjadi tanggung jawab DPR karena peristiwa ini terjadi pada saat masyarakat melakukan demo terhadap DPr.
Tentu kita patut curigai ada yang menggerakan dan memerintahkan itu semua. Nah, ini yang harus dimintai pertanggungjawaban secara publik. Sehingga aparat kepolisian dalam menangani massa aksi harus menggunakan pendekatan yang humanis. Mereka juga bagian dari masyarakat yang sebagian kebebasannya diambil karena ikatan institusi.
Alih-alih ucapan belasungkawa dari para anggota DPR terhadap tragedi kemanusian itu hal yang manusiawi. Masyarakat harus tetap fokus kembali ke tujuan awal aksi yaitu DPR atas kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada rakyat. Jangan sampai masyarakat sipil digiring untuk pengalihan isu.
Kritikan dan masukan dari masyarakat itu menjadi tanda bahwa masyarakat tidak “tidur” dan selama ini ternyata ada kebijakan-kebijakan yang diam-diam dikeluarkan itu tidak berpihak pada masyarakat. Jangan menganggap masyarakat adalah musuh.
Tapi jadikan masyarakat sebagai partner diskusi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR adalah masyarakat itu menerima kebijakan dengan suka cita, taat pada kebijakan dan tidak digugat melalui jalur hukum. (*)