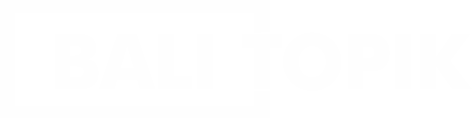Balitopik.com – Tahun ini Indonesia mencapai usia yang tidak muda lagi, delapan puluh tahun sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan dengan penuh getar pada 17 Agustus 1945. Usia yang bila disandingkan dengan manusia, ibarat kakek atau nenek yang seharusnya matang dalam kebijaksanaan, mapan dalam kesejahteraan, dan teduh dalam pelukan sejarah.
Namun, seperti pepatah tua, usia tidak selalu sejalan dengan kualitas hidup. Pada momen sakral HUT RI ke-80 ini, saya sering merenung, sudahkah kemerdekaan benar-benar menjadi milik semua rakyat? Ataukah ia hanya bendera yang berkibar, sementara sebagian saudara kita masih menunduk di bawah beban kemiskinan.
Saya teringat pengalaman pribadi ketika beberapa bulan lalu ikut kegiatan di sebuah desa pinggiran di Bali. Di sana, saya berjumpa dengan seorang ibu paruh baya, wajahnya legam terbakar matahari, tangannya kasar oleh kerja sawah dan cuci pakaian tetangga.
Dengan senyum ia berkata, “Kami sudah merdeka, Nak, tapi kalau soal makan, sekolah anak, dan biaya berobat, kadang masih terasa dijajah keadaan.” Kalimat sederhana itu menampar saya lebih keras daripada seribu pidato kenegaraan. Merdeka ternyata tidak hanya soal bebas dari penjajahan asing, melainkan juga bebas dari jerat lapar, bebas dari kebodohan, dan bebas dari ketidakadilan ekonomi.
Ketika Soekarno berpidato di Sidang BPUPKI, ia berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu dasar negara. Dalam pikirannya, kemerdekaan bukanlah pintu akhir, melainkan gerbang awal menuju masyarakat adil dan makmur. Saya lalu teringat filsuf Karl Marx yang menyinggung bagaimana kemiskinan struktural adalah buah dari sistem yang timpang, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang.
Walau konteksnya berbeda, inti pesannya sama, kemerdekaan politik akan sia-sia jika rakyat tetap terjerat kemiskinan. Sementara itu, filsuf Albert Camus pernah menulis bahwa pemberontakan lahir dari rasa manusia akan absurditas hidup—dan bagi rakyat miskin, absurditas itu nyata ketika melihat upacara bendera meriah, sementara di rumahnya dapur tak berasap.
Pada usia 80 tahun ini, Indonesia memang patut berbangga. Infrastruktur berkembang, teknologi digital merambah hingga desa, kelas menengah tumbuh, dan panggung dunia mulai menoleh pada kita. Namun, kebanggaan itu sering terasa getir ketika saya melihat kontrasnya.
Di kota besar, saya menyaksikan gedung pencakar langit dengan lampu neon yang tak pernah padam, sementara hanya beberapa kilometer dari sana, ada keluarga yang hidup di kolong jembatan, beralaskan kardus, menatap malam dengan perut keroncongan.
Seperti kata Mahatma Gandhi, “Kemiskinan adalah bentuk kekerasan paling buruk.” Kekerasan yang senyap, yang tidak selalu diberitakan, tetapi menghancurkan harkat manusia secara perlahan.
Pengalaman pribadi lainnya kembali menghantui ingatan saya. Seorang sahabat semasa kecil yang sangat cerdas, tetapi terpaksa putus sekolah setelah SMP karena orang tuanya tak mampu membiayai. Ia kemudian bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan. Setiap kali kami bertemu, ia bercanda, tetapi saya tahu matanya menyimpan kesedihan yang dalam.
Di usia 80 tahun merdeka ini, harusnya cerita seperti itu semakin jarang terdengar. Tetapi faktanya, data Badan Pusat Statistik masih menunjukkan jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah ini yang dimaksud “kemerdekaan penuh”?
Sebagai individu yang menikmati kemudahan pendidikan dan akses teknologi, saya sering merasa bersalah. Saya teringat ajaran filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau yang menulis, “Manusia dilahirkan merdeka, tetapi di mana-mana ia terbelenggu.” Kata-kata itu seolah hidup kembali di negeri ini.
Kita merdeka di atas kertas, namun belenggu kemiskinan, korupsi, dan ketidakmerataan masih membatasi langkah jutaan rakyat. Saya pun bertanya pada diri sendiri. apa arti mengibarkan bendera setiap tahun bila tetangga masih sulit membeli beras? Apa arti menyanyikan “Indonesia Raya” dengan lantang bila anak-anak miskin masih putus sekolah?
Namun saya tidak ingin jatuh ke dalam pesimisme semata. Seperti kata Soe Hok Gie, “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.” Maka, dalam melihat HUT RI ke-80, saya ingin menegaskan bahwa kritik lahir dari cinta.
Kita mencintai negeri ini, sehingga kita berani menyorot luka-lukanya. Kemiskinan bukanlah takdir abadi,ia adalah persoalan struktural yang bisa diubah bila ada keberanian politik, keberpihakan ekonomi, dan kesadaran sosial dari kita semua.
Saya percaya pada pandangan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, yang menyatakan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar pertumbuhan angka, melainkan pelebaran kebebasan, kebebasan dari kelaparan, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan untuk hidup bermartabat.
Maka, di usia ke-80 ini, kemerdekaan seharusnya dirayakan bukan hanya dengan karnaval dan panjat pinang. Kemerdekaan sejati dirayakan ketika seorang ibu miskin tak lagi cemas soal biaya melahirkan, ketika seorang anak di pelosok Papua atau NTT bisa belajar dengan buku yang layak, ketika seorang bapak buruh tani merasa penghasilannya cukup untuk menyekolahkan anak sampai universitas.
Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya, hadir dalam perut kenyang rakyat, dalam wajah anak-anak yang ceria, dalam keyakinan bahwa negara tidak meninggalkan yang lemah.
Saya tahu, menulis opini seperti ini mungkin terdengar klise, bahkan idealis. Tetapi saya percaya, bangsa yang besar harus berani bercermin, meskipun wajahnya penuh noda. Delapan puluh tahun merdeka adalah momen refleksi, apakah kita sudah menepati janji yang terkandung dalam teks proklamasi dan Pancasila? Ataukah kita hanya mengulang seremoni tanpa menyentuh substansi? Bila generasi muda hanya diwarisi upacara tanpa perubahan nyata, maka HUT ke-80 hanyalah angka, bukan lompatan sejarah.
Di akhir renungan ini, saya kembali teringat ibu petani di desa yang saya temui dulu. Ia menatap merah putih dengan penuh harap, meskipun hidupnya serba kekurangan. Harapan itu yang membuat saya percaya bahwa bangsa ini masih punya energi untuk bangkit.
Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Selama matahari masih terbit dan tenggelam, perjuangan manusia untuk hidup tidak akan pernah berhenti.” Maka, marilah kita merayakan HUT RI ke-80 bukan hanya dengan pesta, melainkan dengan tekad kolektif untuk mengentaskan kemiskinan. Karena hanya dengan itu, kemerdekaan benar-benar bermakna. (*)
TENTANG PENULIS
Inosius Pati Wedu: Seorang Buruh, Pegiat Literasi dan Aktivis Sosial