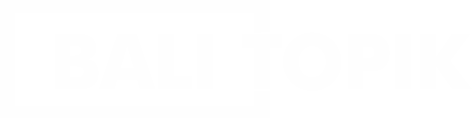Oleh: Yoh. Sandriano N. Hitang
Balitopik.com – Di tengah gegap gempita transisi energi bersih yang digaungkan pemerintah Indonesia, proyek panas bumi di Flores muncul sebagai salah satu wacana yang kontroversial. Flores, dengan potensi geothermal yang melimpah, seharusnya menjadi contoh sukses pengembangan energi hijau. Namun, kenyataannya, proyek ini justru memicu resistensi keras dari masyarakat lokal, mulai dari pemuka agama hingga komunitas adat yang telah lama menjaga harmoninya dengan alam.
Penolakan ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan sebuah perlawanan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, dan ekologis. Konflik ini menegaskan dilema besar antara kebutuhan pembangunan energi bersih dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan hidup.
Antara Potensi dan Tantangan Panas Bumi di Flores
Panas bumi menjadi salah satu pilar utama dalam strategi transisi energi nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam dokumen Indonesia Energy Transition Outlook 2025 yang menempatkan energi terbarukan sebagai kunci pengurangan emisi karbon. Flores, khususnya wilayah Manggarai dan sekitarnya, memiliki potensi geothermal yang signifikan.
Berdasarkan data terbaru PLN Unit Induk Wilayah NTT, pemanfaatan energi panas bumi di Flores mencapai 18 MW dari total potensi sebesar 377 MW. Potensi ini menjadikan Flores sebagai wilayah strategis dalam peta pengembangan energi panas bumi nasional. Hingga kini, bauran energi sistem kelistrikan di Flores menunjukkan dominasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 14,4 persen, diikuti PLTU 13,4 persen, PLTD 6,5 persen, PLTA 1,9 persen, dan PLTMH 3,5 %.
Namun, potensi besar ini tidak serta-merta diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat lokal. Resistensi masyarakat muncul dari kekhawatiran terkait dampak ekologis dan sosial yang telah dan berpotensi terjadi. Kerusakan lingkungan, hilangnya sumber mata pencaharian tradisional, serta ketidakpastian terhadap keberlanjutan dan manfaat jangka panjang proyek menjadi alasan utama penolakan.
Selain itu, kurangnya dialog yang inklusif dan transparan antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat adat memperparah ketegangan yang ada. Resistensi ini bukan sekadar penolakan terhadap teknologi atau pembangunan, melainkan sebuah panggilan untuk pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menghormati kearifan lokal masyarakat setempat.
Dampak Sosial-Ekologis dan Krisis Legitimasi dalam Proyek Panas Bumi
Bagi masyarakat adat Flores, tanah, air, dan hutan bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas kultural dan spiritual mereka. Dalam kerangka ini, proyek panas bumi yang melibatkan eksplorasi dan pengeboran dinilai sebagai ancaman langsung terhadap ekosistem yang selama ini menopang keberlangsungan hidup komunitas lokal.
Kerusakan hutan dan pencemaran sumber air menjadi kekhawatiran utama, karena dapat memicu runtuhnya sistem penghidupan tradisional seperti pertanian dan perikanan. Tak hanya itu, gangguan terhadap keseimbangan ekologis juga menyimpan risiko bencana lanjutan seperti erosi dan penurunan kualitas tanah yang berjangka panjang.
Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa dasar. Laporan CELIOS dan WALHI (2024) mengungkapkan bahwa di tiga lokasi proyek PLTP di NTT – Wae Sano, Sokoria, dan Ulumbu – potensi kehilangan pendapatan petani pada tahap konstruksi dapat mencapai Rp470 miliar. Sementara pada tahun kedua operasi, kerugian terhadap output ekonomi daerah diperkirakan menembus Rp1,09 triliun, disertai ancaman penurunan jumlah tenaga kerja hingga 50.608 orang di tahun kedua. Angka-angka ini mencerminkan betapa eksplorasi panas bumi tidak hanya menekan keberlangsungan ekologis, tetapi juga berpotensi merusak fondasi ekonomi masyarakat lokal.
Di sisi lain, persoalan legitimasi semakin menguat ketika proyek-proyek tersebut dijalankan dengan minim keterlibatan warga. Banyak masyarakat adat merasa dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan, meski wilayah yang digunakan merupakan tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Siaran pers Koalisi Warga Flores–Lembata (2023) yang di publikasikan oleh JATAM (11/07/2025) menyoroti kurangnya transparansi serta absennya mekanisme konsultasi yang bermakna. Ketika hak atas informasi dan partisipasi diabaikan, proyek yang semula dimaksudkan sebagai solusi energi justru menjelma menjadi sumber konflik sosial.
Selain kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial, keraguan publik juga tumbuh terhadap manfaat jangka panjang dari proyek panas bumi. Banyak warga mempertanyakan, apakah listrik yang dihasilkan akan benar-benar menopang kesejahteraan masyarakat lokal, atau sekadar menguntungkan segelintir pemodal. Dalam laporan CELIOS–WALHI juga ditegaskan bahwa proses ekstraksi geothermal bersifat ekstraktif dan padat modal, sehingga rentan dimonopoli oleh korporasi besar dan asing – sementara warga lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Tanpa adanya jaminan keberlanjutan dan pengelolaan yang inklusif, proyek panas bumi di Flores bukan hanya berisiko merusak lingkungan hidup, tetapi juga dapat mewariskan ketimpangan sosial yang lebih dalam. Oleh karena itu, tuntutan warga agar hak atas tanah, air, dan kehormatan budaya diakui secara utuh bukan sekadar penolakan proyek, melainkan seruan akan bentuk pembangunan yang lebih adil dan manusiawi.
Merawat Legitimasi, Menata Ulang Energi Bersih yang Berkeadilan
Transisi energi bukan sekadar peralihan teknologi, tetapi juga upaya memantik perubahan sosial. Keberhasilan transisi tak cukup diukur dari berapa banyak megawatt listrik dihasilkan atau berapa besar emisi berhasil ditekan, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Artinya, transisi energi hanya akan efektif bila didukung oleh legitimasi sosial yang kuat.
Kelemahan banyak proyek energi di Indonesia, termasuk di Flores, terletak pada pendekatan yang top-down. Masyarakat sering kali diposisikan sebagai pelengkap, bukan mitra. Padahal, tanpa rasa memiliki, sulit mengharapkan dukungan jangka panjang. Jika negara ingin mempercepat transisi energi, maka perlu memperlambat proses di awal untuk mendengar, menjelaskan, dan menyusun kebijakan yang kontekstual. Tanpa ruang dialog yang sejajar, proyek panas bumi hanya akan menghadapi krisis legitimasi.
Di Flores, proyek-proyek panas bumi lebih banyak menumbuhkan kekhawatiran dibandingkan harapan. Untuk mengatasi konflik dan resistensi yang terjadi, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Pemerintah dan pelaku industri harus membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan dengan masyarakat adat Flores. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan mereka secara aktif, menghormati hak atas tanah adat, dan mengakomodasi aspirasi serta kearifan lokal. Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan energi yang berkeadilan sosial.
Pendekatan co-management yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya panas bumi harus diimplementasikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi proyek, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pemerintah perlu menetapkan standar ketat terkait dampak lingkungan dan sosial, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat lokal.
Manfaat ekonomi dari proyek panas bumi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan kesempatan kerja. Transparansi dalam pengelolaan dana dan keuntungan proyek menjadi kunci untuk mencegah ketimpangan dan konflik sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa energi bersih tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat adat.
Pengalaman Flores mengingatkan kita bahwa energi bersih panas bumi tidak serta merta berarti adil. Di wilayah yang kaya akan sumber daya, justru terjadi kelangkaan dialog, ketertutupan informasi, dan ketimpangan relasi. Transisi energi yang semula dirancang sebagai jalan keluar dari krisis iklim, berubah menjadi sumber ketegangan baru ketika dijalankan tanpa kepekaan sosial.
Untuk itu, arah transisi energi nasional perlu ditata ulang. Transisi energi mesti menempatkan masyarakat sebagai poros perubahan. Prinsip transisi harus bergeser dari sekadar efisiensi dan percepatan, menjadi keadilan dan keterlibatan.
Transisi energi yang berkeadilan menuntut kebijakan yang merangkul keberagaman perspektif, bukan menihilkan suara lokal demi efisiensi semata. Keberadaan masyarakat adat Flores bukanlah hambatan, melainkan fondasi untuk membangun solusi inovatif yang selaras dengan alam. Dengan melibatkan mereka sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, kita dapat menciptakan model pengelolaan panas bumi yang memadukan teknologi mutakhir dan kearifan tradisional. Kita tak bisa menyelamatkan lingkungan hanya dengan mengorbankan komunitas yang telah menjaganya selama ini.
Energi bersih yang adil bukan utopia. Ia hanya membutuhkan satu syarat utama: keberanian untuk mendengar dan kerendahan hati untuk membangun bersama. Di situlah, sesungguhnya, energi masa depan kita bertumpu. (*)
Tentang Penulis
Yoh. Sandriano N. Hitang adalah Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain itu penulis adalah Mantan Ketua PMKRI Denpasar Sanctus Paulus Periode 2016/2017.