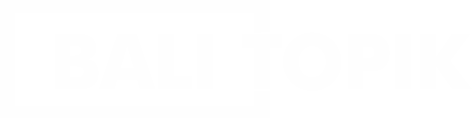Oleh: Andrianus Yovianto – Kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar.
Balitopik.com – Politik dinasti akhir-akhir ini begitu sering dibicarakan dalam lingkup masyarakat. Dalam hal berdemokrasi, politik dinasti menjadi persoalan dalam menghasilkan pemimpin yang punya kemampuan dan kompeten dalam bidangnya, dan hal inilah yang merusak citra demokrasi itu sendiri, terutama dalam konstelasi pilkada yang akan datang.
Berdasarkan data di tahun 2024 sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 november 2024.
Indonesia sendiri menjadi negara demokrasi terbesar ketiga didunia dan hal ini tidak luput dari praktik politik dinasti. Di Indonesia praktik politik dinasti muncul sejak orde baru, dimana saat itu presiden Soeharto mengangkat putrinya sendiri yaitu Siti Hardiyanti Rukmana untuk menduduki jabatan strategis sebagai menteri sosial.
Hal ini menjadi sebuah penghantar politik dinasti di era reformasi sehingga di era reformasi tidak luput dari praktik politik dinasti yang begitu merajalela.
Politik dinasti merupakan sebuah upaya dimana adanya usaha untuk mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak baik, seperti mengedepankan kepentingan keluarga sendiri, dan menyalahgunakan kewenangan sehingga tercapainya kepentingan pribadi dan golongan tertentu.
Penerapan desentralisasi dan pemberian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia, praktik politik dinasti kian semakin berkembang. Namun, perbedaannya jika pada saat orde baru praktik dinasti politik lebih masif terjadi pada tingkat pusat, maka pasca reformasi praktik politik dinasti lebih masif terjadi di tingkat daerah dalam praktik pilkada.
Terlebih lagi, setelah adanya mekanisme pilkada secara langsung pada tahun 2005 lalu. Tentu hal ini menjadi peluang bagi sekelompok orang yang memiliki kepentingan terutama dalam kontestasi pilkada yang mendatang.
Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga munculnya politik dinasti antara lain;
1. Sentralisasi Politik. Pengendalian politik dilakukan secara satu arah dari atas ke bawah dan akibatnya tokoh politik lokal di paksakan untuk harus mengikuti arahan dari elite politik pusat. Akibat dari hal itu, kontestasi pilkada tidak semata-mata menjadi pertarungan tokoh di daerah, melainkan elite di tingkat pusat.
2. Kandidasi politik yang cenderung tertutup. Dalam praktiknya, pencalonan kepala daerah oleh partai memiliki banyak pertimbangan yang tidak digubris di ruang publik. Akibatnya, publik hanya menjadi subjek pasif dalam memilih calon yang telah ditentukan oleh partai.
3. Persoalan kaderisasi menjadi suatu hal yang mendorong munculnya politik dinasti. Persoalan kaderisasi juga sangat kompleks dalam mendorong lahirnya praktik politik dinasti. Kegagalan partai dalam menghasilkan kader yang memiliki kualitas berdampak pada dipilihnya jalan pintas dengan meminang calon yang memiliki popularitas. Pada beberapa wilayah, popularitas jamak dimiliki oleh keturunan tokoh politik, baik dalam elite lokal maupun nasional.
Pada dasarnya ada upaya menghambat politik dinasti melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
Namun, pengaturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.33/PUU/XIII/2015 lantaran dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945.
Munculnya politik dinasti memiliki dampak yang sangat krusial seperti, lahirnya oligarki pada kondisi yang akan datang. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi sekaligus menghambat proses konsolidasi demokrasi.
Dari sisi internal pemerintah, lahirnya politik dinasti akan menyebabkan kemandekan sirkulasi kekuasaan. Peralihan kekuasaan hanya akan berputar pada lingkungan elite semata dan juga penyimpangan kekuasan seperti, korupsi, kolusi dan nepotisme akan meningkat. Selain itu juga proses kaderisasi politik juga akan sendirinya hilang dengan adanya praktik politik dinasti.
Jika dilihat berdasarkan data yang dimiliki Prof Djohermansyah Djhoan dalam pilkada 2024 yang berafiliasi dengan politik dinasti , terdapat 175 kasus atau 32 persen politik dinasti, tentu hal ini menjadi suatu hal yang sangat disayangkan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.
Dalam pilkada di tahun 2024 ini tentu sangat disayangkan jika masih banyak lagi yang terafiliasi dengan politik dinasti, tentu ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang seutuhnya, dan hal ini juga sangat berpengaruh pada kualitas dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam melahirkan sebuah kebijakan.
Namun jika dibiarkan politik dinasti tentu sangat berpengaruh pada masyarakat banyak dan juga yang menjadi korban adalah masyarakat karena seorang pemimpin yang terlahir dari politik dinasti akan menjadi pemimpin yang arogan dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan masyarakat umum.
Oleh karena itu politik dinasti harus dihilangkan dari demokrasi di Indonesia karena membawa dampak yang krusial kepada masyarakat. (*)